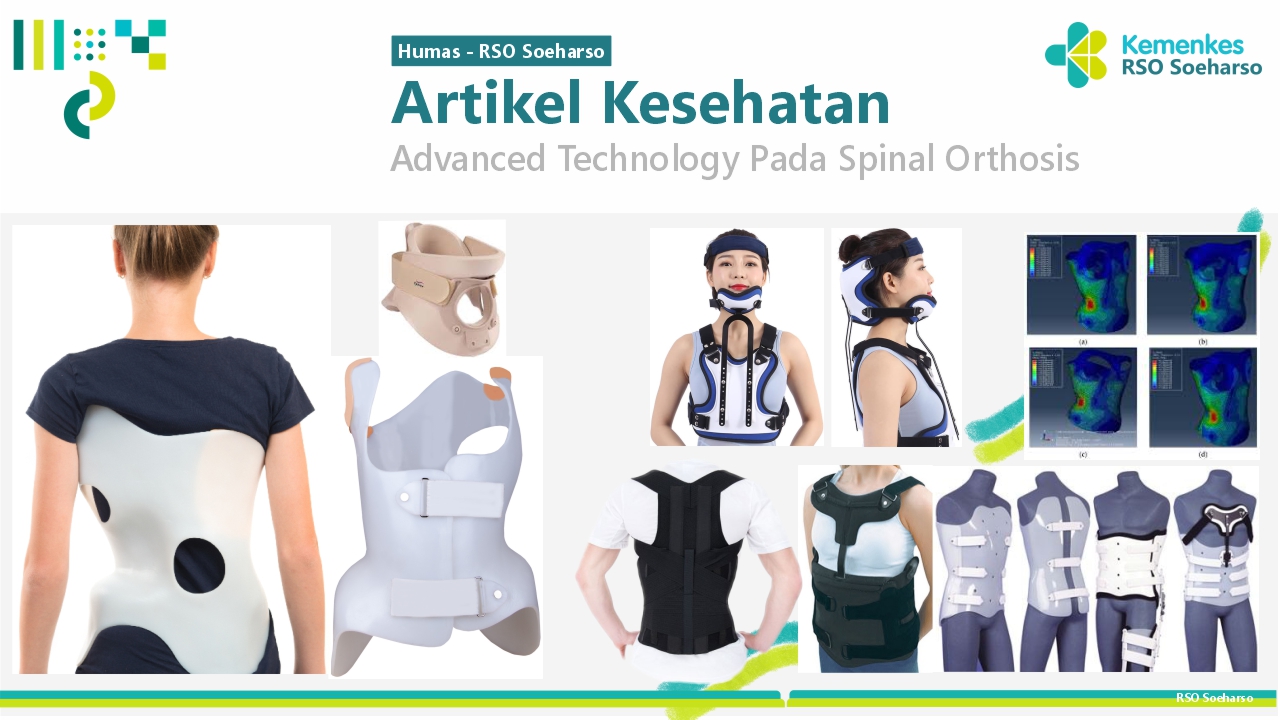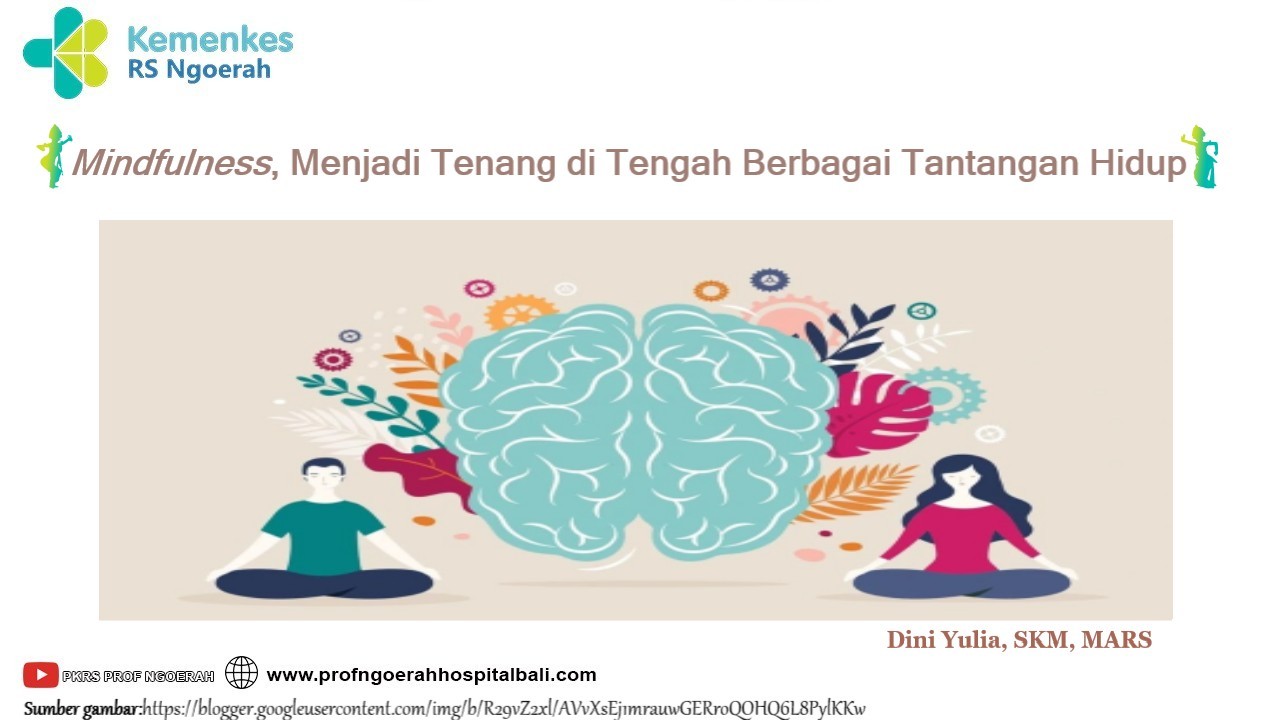Mengompol pada Lansia

Mengompol atau keluarnya air seni (urine) di luar kehendak/ tanpa disadari (inkontinensia urine), seringkali disalahpersepsikan sebagai kondisi yang wajar terjadi pada orang berusia lanjut (lanjut usia/ lansia). Kondisi ini sejatinya bukanlah suatu hal yang normal, meskipun terjadi peningkatan risiko terjadinya mengompol seiring dengan proses menua pada sistem urogenital (perubahan pada struktur kandung kemih dan saluran kemih bagian bawah, fungsi berkemih, kadar hormon, dan persarafan). Di sisi lain, lansia mungkin memiliki penyakit (diabetes melitus/ kencing manis, penyakit sendi sehingga membatasi pergerakan, stroke, penyakit Parkinson, demensia/ pikun, depresi, dan lain-lain) yang dapat menimbulkan atau memperburuk kondisi mengompol.
Kejadian mengompol 1,3–2 kali lebih banyak pada perempuan dibandingkan lelaki, dan semakin meningkat dengan bertambahnya usia dan kerentaan. Survei terhadap 523 pasien di Poliklinik Geriatri di 6 rumah sakit Pendidikan di Indonesia menunjukkan 11,1% pasien mengalami overactive bladder (OAB) dan 22,2% terdapat keluhan mengompol: 56,9% terjadi pada perempuan, 42,2% mengalami mengompol tipe desakan, 21,6% tipe tekanan, 1,7% tipe luapan, dan 18,1% tipe campuran. Median total biaya yang dikeluarkan terkait dengan masalah OAB di Poliklinik Geriatri dan Uroginekologi RS Cipto Mangunkusumo pada bulan Juli 2005– Maret 2006 sebesar Rp 2.850.000 per tahun per pasien.
Mengompol dapat berdampak pada masalah medis, sosial-ekonomi, dan kualitas hidup. Oleh karena itu, salah satu aspek kesehatan yang harus dievaluasi pada lansia adalah ada tidaknya keluhan mengompol. Pendekatan klinis mengompol lazimnya diawali dengan pertanyaan apakah ada keluhan mengompol. Jika ada keluhan mengompol, sejak kapan terjadi, deskripsi keluhan, dan kondisi apa yang menyertai keluhan mengompol. Pasien atau keluarga pasien diminta untuk mengisi catatan harian berkemih (bladder diary) agar dapat diketahui waktu, jumlah, jenis, dan distribusi asupan cairan serta frekuensi dan waktu pasien berkemih dengan atau tanpa disertai mengompol. Selain itu, dilalukan evaluasi menyeluruh (pengkajian paripurna pasien geriatri) mencakup aspek medis, penyakit penyerta, obat-obat yang dikonsumsi, fungsi fisik/ status fungsional (kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari, seperti makan, mandi, dan berjalan), kemampuan daya pikir, psikologis, status gizi, status kerentaan, kualitas hidup, dan kondisi sosial-ekonomi. Pemeriksaan fisik dan penunjang dilakukan sesuai indikasi medis.
Mengompol dapat terjadi secara akut/ mendadak akibat kondisi tertentu sehingga apabila kondisi penyebab teratasi, maka mengompol juga akan teratasi. Kondisi yang dapat menyebabkan keluhan mengompol mendadak tersebut antara lain: delirium (perubahan kesadaran), infeksi (infeksi saluran kemih), masalah psikologis (misalnya depresi), efek samping obat (misalnya obat bersifat diuretika untuk mengeluarkan cairan dari tubuh sehingga pasien menjadi sering berkemih), kadar glukosa darah yang tinggi sehingga menjadi sering berkemih, keterbatasan untuk mobilitas/ bergerak, dan impaksi tinja akibat sembelit. Mengompol juga dapat berlangsung lama dan menetap (persisten) yang dapat dibedakan menjadi beberapa tipe:
- Tekanan: keluarnya urine tanpa disadari pada saat bersin, batuk, atau aktivitas fisik; umumnya akibat kelemahan otot dasar panggul.
- Desakan: keluarnya urine tanpa disadari yang diawali oleh desakan berkemih; lazimnya akibat OAB sehingga lansia mengalami desakan untuk berkemih yang tidak wajar, berupa peningkatan frekuensi berkemih hingga ?8 kali sejak bangun tidur di pagi hari hingga menjelang tidur malam dan >1 kali saat malam hari (nokturia).
- Luapan: keluarnya urine tanpa disadari yang ditandai dengan gejala kandung kemih penuh secara berlebihan; lazimnya akibat sumbatan parsial pada leher kandung kemih (misalnya akibat pembesaran kelenjar prostat) atau penurunan kemampuan kontraksi otot kandung kemih, sehingga urine cenderung tertahan di dalam kandung kemih (retensi urine) sehingga meningkatkan risiko terjadinya infeksi saluran kemih.
- Fungsional: keluarnya urine tanpa disadari akibat ketidakmampuan fungsional untuk ke toilet, seperti hendaya mobilitas atau kognitif (pikun).
- Campuran: keluarnya urine tanpa disadari kombinasi dari beberapa tipe mengompol; lazimnya kombinasi tipe tekanan dan desakan.
Kondisi mengompol yang persisten tersebut juga dapat diperburuk oleh kondisi akut seperti yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya.
Prinsip tata laksana mengompol pada lansia mengacu pada tipe mengompol dan status fungsional (tingkat kemandirian dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari). Misalnya latihan penguatan otot dasar panggul (latihan Kegel) pada mengompol tipe tekanan atau berkemih dengan terjadwal pada mengompol tipe fungional pada pasien yang pikun atau terapi obat untuk merelaksasi otot kandung kemih pada mengompol tipe desakan akibat OAB. Terapi obat diupayakan baru dimulai bila tata laksana non-obat belum memberikan hasil.
Perlu dikaji ulang dan tata laksana penyakit penyerta yang mungkin menyebabkan kondisi mengompol belum membaik. Telaah obat-obatan yang dikonsumsi dan tata laksana kondisi sembelit yang mungkin berkontribusi pada keluhan mengompol pasien. Pasien dirujuk ke dokter spesialis terkait sesuai dengan penyakit/ penyebab mengompol dan preferensi pasien atau keluarga pasien.
Referensi:
<!--[if !supportLists]-->Vaughan CP, Johnson TM. Incontinence. In: Halter JB, Ouslander JG, Studenski S, High KP, Asthana S, Ritchie CS, et al. Hazzard’s geriatric medicine and gerontology. USA. McGraw-Hill. 2017. p. 801–19.
Sumardi R, Mochtar CA, Junizaf, Santoso BI, Setiati S, Nuhonni SA, Trihono PP, Rahardjo HE, Syahputra FA. Prevalence of urinary incontinence, risk factors, and its impact: multivariate analysis from Indonesian nationwide survey. Acta Med Indones-Indones J Intern Med. 2014;46(3):175–82.
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->Setiati S, Santoso B, Istanti R. Estimating the annual cost of overactive bladder in Indonesia. Acta Med Indones-Indones J. Intern Med. 2006;38(4):189–92.
Burkhard FC, Bosch JLHR, Cruz F, Lemack GE, Nambiar AK, Thiruchelvam N, et al. EAU guidelines: urinary incontinence. Amsterdam: European Association of Urology. 2020. ISBN 978-94-92671-07-3
<!--[if !supportLists]-->DuBeau CA, Kuchel GA, Johnson T, Palmer MH, Wagg A. Incontinence in the frail elderly. In: Paul A, Linda C, Saad K, Alan W. Incontinence 4th Edition. 2009. p. 961–1011.
<!--[if !supportLists]-->Perkumpulan Kontinensia Indonesia (PERKINA). Panduan tata laksana inkontinensia urine pada dewasa. 3rd ed. Mochtar AC, editor. Jakarta: Ikatan Ahli Urologi Indonesia; 2022. p.127–71.
Sumber gambar: https://mhomecare.co.id/blog/wp-content/uploads/2021/02/Penyebab-dan-cara-mengatasi-lansia-sering-ngompol-750x424.webp